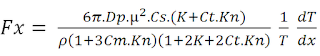Dalam ilmu
perpindahan kalor fouling adalah pembentukan lapisan deposit pada permukaan
perpindahan panas dari bahan atau senyawa yang tidak diinginkan. Bahan atau
senyawa itu berupa kristal, sedimen, senyawa biologi, produk reaksi kimia,
ataupun korosi. Pembentukan lapisan deposit ini akan terus berkembang selama
alat penukar kalor dioperasikan. Akumulasi deposit pada permukaan alat
penukar kalor menimbulkan kenaikan pressure drop dan menurunkan
efisiensi perpindahan panas. Untuk menghindari penurunan performance
alat penukar kalor yang terus berlanjut dan terjadinya unpredictable cleaning,
maka diperlukan suatu informasi yang jelas tentang tingkat
pengotoran untuk menentukan jadwal pembersihan (cleaning schedule).
Lapisan fouling dapat berasal
dari partikel-partikel atau senyawa lainnya yang terangkut oleh aliran fluida.
Pertumbuhan lapisan tersebut dapat meningkat apabila permukaan deposit yang
terbentuk mempunyai sifat adhesif yang cukup kuat. Gradien temperatur yang
cukup besar antara aliran dengan permukaan dapat juga meningkatkan
kecepatan pertumbuhan deposit. Pada umumnya proses pembentukan lapisan fouling
merupakan phenomena yang sangat kompleks sehingga sukar sekali dianalisa secara
analitik. Mekanisme pembentukannya sangat beragam, dan metode-metode
pendekatannya juga berbeda-beda
Proses Pembentukan
Berdasarkan proses terbentuknya
endapan atau kotoran, faktor pengotoran dibagi 5 jenis, yaitu :
1. Pengotoran
akibat pengendapan zat padat dalam larutan (precipitation fouling).
Pengotoran ini
biasanya terjadi pada fluida yang mengandung garam-garam yang terendapkan pada
suhu tinggi, seperti garam kalsium sulfat, dll.
2. Pengotoran
akibat pengendapan partikel padat dalam fluida (particulate fouling).
Pengotoran ini
terjadi akibat pengumpulan partikel-partikel padat yang terbawa oleh
fluida di atas permukaan perpindahan panas, seperti debu, pasir, dll.
3. Pengotoran
akibat reaksi kimia (chemical reaction fouling).
Pengotoran
terjadi akibat reaksi kimia di dalam fluida, di atas permukaan perpindahan
panas, dimana material bahan permukaan perpindahan panas tidak ikut bereaksi,
seperti adanya reaksi polimerisasi, dll.
4. Pengotoran
akibat korosi (corrosion fouling).
Pengotoran terjadi
akibat reaksi kimia antara fluida kerja dengan material bahan permukaan
perpindahan panas.
5. Pengotoran
akibat aktifitas biologi (biological fouling).
Pengotoran ini
berhubungan dengan akitifitas organisme biologi yang terdapat atau terbawa
dalam aliran fluida seperti lumut, jamur, dll.
Akibat pembentukan fouling
tersebut, maka kemampuan alat penukar kalor akan mengalami penurunan. Dalam
beberapa kasus, pembersihan lapisan fouling dilakukan secara kimia dan mekanis.
Salah satu cara mekanis yang umum dilakukan adalah dengan metode on-line
cleaning dengan menggunakan bola taprogge
Mekanisme Terjadinya Fouling
Pada umumnya mekanisme terjadinya
fouling, pembentukan dan pertumbuhan deposit, terdiri dari :
a.
Initiation, pada periode kristis dimana temperatur, konsentrasi dan
gradien kecepatan, zona deplesi oksigen dan kristal terbentuk dalam waktu yang
singkat.
b. Transport
partikel ke permukaan
·
secara
mekanik = imfaction
·
secara
turbulen = difusion
·
Thermophoresis dan Electrophoresis
c. Adhesi dan
Kohesi pada permukaan.
d.
Migration, berupa perpindahan foulant (bahan atau senyawa penyebab fouling)
menuju ke permukaan, dan berbagai
mekanisme perpindahan difusi.
e. Attchment,
Awal dari terbentuknya lapisan deposit.
f.
Transformation or Aging, periode kristis dimana perubahan fisik ataupun
struktur kimia/kristal dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan lapisan
deposit.
g. Removal or
Re-entrainment, perpindahan lapisan fouling dengan cara pemutusan, erosi atau
spalling.
Kecepatan aliran dan
temperatur fluida (atau beda temperatur) dapat menjadi variabel signifikan
terjadinya fouling. Peningkatan kecepatan menyebabkan transfer massa spesies
fouling dapat meningkat, seiring dengan terbentuknya deposit pada
permukaan perpindahan kalor. Secara terus menerus, shear force pada
fluida/permukaan perpindahan kalor meningkat, melalui mekanisme removal
deposit. Temperatur yang digunakan pada alat penukar kalor dapat mempengaruhi
besarnya luasan fouling pada permukaan perpindahan kalor.
Kondisi Terjadinya Fouling
Kondisi yang mempengaruhi
terjadinya fouling yaitu :
1. Parameter
operasi alat penukar kalor, yaitu: velocity, surface tempareture,
dan fluids temperature.
2. Parameter
alat penukar kalor, yaitu: Konfigurasi alat penukar kalor, permukaan material,
dan struktur permukaan.
3. Fluids
properties, yaitu : Suspended solid, Dissolved solid, Dissolved gases,
dan Trace element.
Deposit partikel pada
permukaan perpindahan kalor banyak dijumpai pada aliran gas-partikel dengan
temperatur tinggi. Proses terjadinya fouling ini dapat ditemukan di power plant
system seperti di economizer, superheater, peralatan penukar kalor pipa air
pendingin, dan beberapa proses di industri kimia. Salah satu contoh adalah
fenomena fouling pada boiler. Partikel yang dikenal dengan fly ash (abu
terbang) berasal dari sisa hasil pembakaran batubara di boiler. Fly ash ini
tersuspensi dalam aliran gas yang kemudian akan masuk ke peralatan penukar
kalor. Aliran gas-fly ash ini akan membentuk lapisan deposit/fouling pada
dinding luar tube.
Tiga modus utama ash transport
dalam pembentukan lapisan deposit yaitu:
1. Inertial
and eddy impaction, modus ash transport ini dapat membentuk tipe fouling
deposit jenis Upstream dan downstream.
2. Vapor-phase
and small-particle diffusion, modus ash transport ini dapat membentuk tipe
deposit jenis Inner Layer.
3. Thermophoresis/Electrophoresis,
modus ash transport ini dapat membentuk tipe deposit jenis Inner Layer.
mekanisme terbentuknya deposite
partikel pada dinding luar tube
Lapisan deposit
paling tebal terdapat pada bagian depan tube (upstream) atau pada sudut 0o.
Jumlah deposit partikel yang jatuh (removed) semakin besar dengan semakin
besarnya sudut sampai pada sudut 90o. Untuk sudut mendekati nol, kecepatan
aliran adalah minimal, sehingga daya lepas deposit partikel (detaching force)
karena aerodynamic force dapat diabaikan (Anatoli D. Zimon). Untuk sudut
mendekati 90o, boleh dibilang hampir semua deposit partikel jatuh, hal ini
disebabkan oleh impact dari pergerakan partikel. Sebaliknya ketika aliran
melalui sisi bagian atas tube, detaching force meningkat sesuai dengan
kecepatan aliran, dimana pada sisi ini kecepatan aliran adalah maksimum.
Setelah deposit
mencapai kondisi jenuh pada waktu tertentu, sejumlah deposit pada bagian depan
(upstream) terjatuh, namun tidak semua bagian dari deposit itu terjatuh.
Setelah itu terbentuk lagi deposit, kemudian setelah mencapai kondisi jenuh,
terjatuh lagi. Fenomena ini terus berulang-ulang, dan keadaan akhir distribusi
ketebalan deposit.
Cara Mengurangi Fouling pada Heat
Exchanger
Berikut ini adalah cara
mengurangi terjadinya fouling pada Heat Exchanger , yaitu :
1. Pemilihan heat
exchanger ( HE ) yang tepat, Penggunaan beberapa tipe HE tertentu dapat mengurangi pembentukan fouling
di karenakan area dead space yang lebih sedikit dibandingkan dengan tipe
yang lainnya, seperti plate dan spiral heat exchanger,
namun begitu jenis HE tersebut hanya dapat menangani design pressure
sampai 20 – 25 bar dan design temperature 250 oC ( plate
) dan 400 oC ( spiral ).
2. Gunakan
diameter tube yang lebih besar. STHE umumnya didesain dengan ukuran tube dari 20 mm atau 25 mm,
untuk penggunaan fluida yang kotor ( fouling resistance
> 0.0004 h-m2 C/kal ) gunakan tube dengan diameter (
minimum ) 25 mm ( outside diameter, OD )
3.
Kecepatan
tinggi, seperti yang
telah di jelaskan di atas bahwa pada kecepatan tinggi, fouling dapat
dikurangi, koefisien heat transfer juga akan semakin tinggi, namun
demikian mengoperasikan HE dengan kecepatan tinggi mengakibatkan pressure
drop yang tinggi pula serta erosi , kenaikan pressure drop lebih
cepat dari pada kenaikan koefisien perpindahan panas, maka perlu dicari
kecepatan yang optimum.
4. Margin pressure drop yang cukup.
Pada HE yang digunakan untuk fluida yang berpotensi membentuk fouling
yang tinggi, disarankan untuk menggunakan margin 30 – 40 % antara pressure
drop yang diijinkan ( allowable ) dengan pressure drop yang
dihitung ( calculated ) hal ini dilakukan untuk antisipasi pressure drop
yang tinggi akibat penggunakan kecepatan yang tinggi.
5. Gunakan tube bundle dan heat
exchanger cadangan. Jika penggunaan HE untuk fluida
yang berpotensi membentuk fouling yang sangat ekstrim, maka tube
bundle candangan sebaiknya digunakan. Jika fouling telah terjadi cukup cepat ( setiap 2 – 3 bulan ) maka
sebaiknya digunakan HE cadangan. STHE cadangan juga diperlukan untuk tipe STHE Fixed
tubesheet ( pembentukan fouling yang tinggi pada tube ,
seperti pada reboiler thermosiphon vertikal yang menggunakan fluida
polimer seperti pada Butadiene plant).
6. Gunakan 2 shell
yang disusun secara paralel. dengan penggunaan STHE dimana Shell disusun secara seri, maka jika salah
satu STHE telah terjadi penumpukan ( akumulasi ) fouling ( dimana STHE
tersebut diservice ) maka STHE yang satunya lagi dapat digunakan, walaupun
tentunya terjadi penurunan output, sebaiknya kapasitas yang digunakan masing-
masing antara 60 – 70 % dari kapasitas total
7.
Gunakan Wire
Fin tube. Penggunaan Wire
fin tube,dapat mengurangi terbentuknya fouling, pada awalnya
penambahan wire fin tube ini digunakan untuk meningkatkan
perpindahan panas tube pada aliran laminar. Wire fin dapat
menaikkan pencampuran radial ( radial mixing ) dari dinding tube hingga
kebagian centre ( tengah ), efek gerakan pengadukan inilah yang dapat
meminimalisasikan deposit pada dinding tube.
8. Gunakan Fluidized Bed HE,
HE tipe ini dapat menghandle fouling yang ekstrim.Apabila Fluida kotor ditempatkan pada shell.
9. Gunakan U-Tube atau Floating head.
Kelemahanan penggunaan U tube
adalah kesulitan pembersihan pada bagian U.
10.
Gunakan susunan
tube secara Square atau Rotate Square. susunan square menyediakan akses yang lebih
sehingga cleaning HE secara mechanical dengan menggunakan Rodding atau
hydrojetting baik pada susunan triangle, namun begitu tube
yang disusun secara square memberikan koefisien heat transfer yang
rendah, untuk situasi seperti ini , maka rotate square dapat digunakan.
11. Meminimalisasikan
dead space dengan desain baffle secara optimum. STHE lebih mudah mengalami Fouling dikarenakan
adanya dead space, oleh sebab itu , penentuan jarak antar baffle ( baffle
spacing ) dan baffle cut sangatlah penting, kedua variable tersebut
sangat berpengaruh dalam pentuan besar kecilnya koefisien perpindan panas pada
shell. Nilai Baffle cut sebaiknya digunakan antara 20 -30 %, dimana baffle cut
sebesar 25 % adalah nilai yang cukup baik sebagai starter. Untuk perpindahan
panas yang hanya melibatkan panas sensible ( seperti heater atau cooler )
disarankan tidak menempatkan posisi baffle secara vertikal, untuk perpindahan
panas yang melibatkan panas laten atau terjadinya perubahan fase ( seperti
condenser, vaporizer ) disarankan untuk menempatkan posisi baffle secara
vertikal.
12. Kecepatan
tinggi, sama seperti pada tube, pengunaan kecepatan tinggi pada
shell akan dapat mengurangi pembentukan fouling, dan dapat menaikkan
koefisien perpindahan panas shell. Kecepatan pada shell umumnya ( disamping
faktor lain seperti tube pitch dan lain –lain ) dipengaruhi oleh
diameter shell dan baffle spacing.
13. Gunakan
tube pitch yang lebih besar untuk fouling yang lebih sangat tinggi.
Umumnya tube pith yang digunakan adalah sebesar 1.25 kali dari OD untuk
triangular pitch dan 6 mm lebih dari OD untuk square.